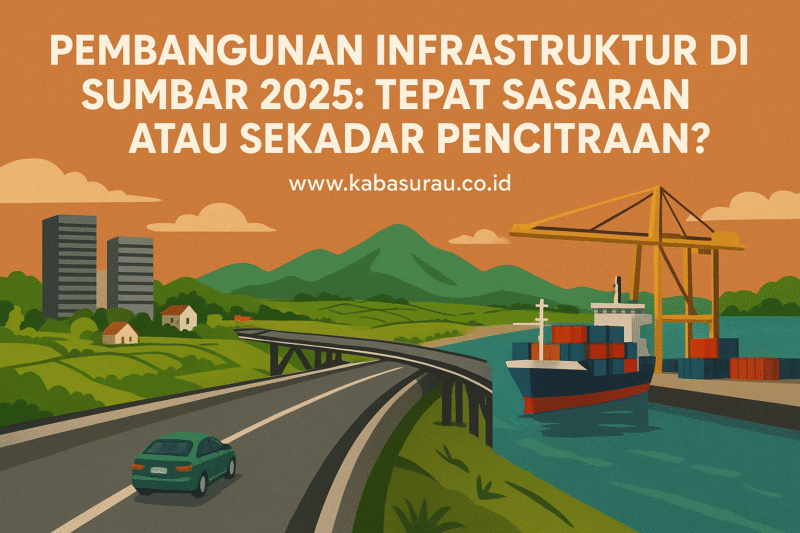Oleh: Muhammad Okta Ilvan, S.Sos
(Opini – Kabasurau.co.id)
Pendahuluan: Infrastruktur sebagai “Obat Mujarab”?
Dalam wacana pembangunan, infrastruktur kerap disebut sebagai “obat mujarab” untuk semua persoalan ekonomi. Jalan tol diyakini akan memangkas waktu tempuh, pelabuhan baru dipercaya bisa membuka jalur perdagangan, dan jembatan megah dianggap simbol kemajuan. Sumatera Barat (Sumbar) pada 2025 tidak ketinggalan dalam euforia ini. Pemerintah provinsi bersama pusat mendorong proyek-proyek strategis mulai dari Jalan Tol Padang–Sicincin, pengembangan Pelabuhan Panasahan di Pesisir Selatan, hingga perencanaan jangka panjang dalam Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) 2025–2034.
Namun, pertanyaan penting muncul: apakah pembangunan infrastruktur di Sumbar tahun 2025 benar-benar tepat sasaran, atau hanya sekadar deretan proyek fisik yang indah dilihat tetapi minim dampak ke masyarakat luas?
Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat lebih jauh: data anggaran, arah kebijakan, dinamika fiskal, serta dampaknya terhadap masyarakat. Artikel ini mencoba menghadirkan analisis kritis, dengan memadukan narasi populer agar mudah dipahami pembaca awam, sekaligus nuansa akademis agar tetap berbobot dan serius.
Gambaran Umum: Ambisi Besar, Dana Terbatas
Secara resmi, RPIW Sumbar 2025–2034 memetakan empat fokus utama pembangunan:
- Perkotaan (PKN Palapa: Padang–Pariaman–Lubuk Alung–Padang Panjang–Bukittinggi) sebagai koridor urban dan ekonomi.
- Pariwisata (KSPN Bukittinggi–Danau Singkarak–Maninjau–Mentawai) sebagai motor pertumbuhan jasa.
- Pertanian dan Pangan (KPPN Agam dan sekitarnya).
- Daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan), terutama Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Visi ini seolah menjanjikan pemerataan: dari kota hingga pelosok, dari pariwisata hingga pertanian. Tetapi di balik visi megah, selalu ada keterbatasan.
APBD Perubahan Sumbar 2025 ditetapkan sekitar Rp6,244 triliun, naik sedikit dari APBD murni. Dari jumlah itu, belanja modal untuk infrastruktur tidak bisa sepenuhnya leluasa, karena sebagian besar sudah terserap untuk belanja pegawai, transfer daerah, dan urusan rutin lain. Ditambah lagi, tingkat ketergantungan fiskal Sumbar terhadap transfer pusat masih tinggi—sebuah sinyal bahwa kemandirian fiskal daerah masih rapuh.
Di sisi lain, proyek strategis seperti Tol Padang–Sicincin (±35,9 km) yang mulai beroperasi pada Agustus 2025 menelan biaya ratusan miliar rupiah, sebagian besar dari anggaran pusat dan BUMN (Hutama Karya). Begitu juga Pelabuhan Panasahan di Painan yang mendapatkan kucuran sekitar Rp97 miliar dari Kementerian Perhubungan. Jadi, benang merahnya jelas: Sumbar memang punya proyek besar, tapi keberlanjutan dan pemerataan manfaatnya masih perlu diuji.
Narasi di Lapangan: Antara Tol, Pelabuhan, dan Jalan Desa
Mari kita turunkan diskusi ini ke realitas sehari-hari.
Bagi warga perkotaan, terutama Padang dan Pariaman, beroperasinya Tol Padang–Sicincin adalah kabar gembira. Waktu tempuh yang dulunya bisa dua jam kini dipangkas hingga setengahnya. Bagi wisatawan dari Bandara Internasional Minangkabau menuju Bukittinggi, tol ini seperti jalan pintas yang memudahkan.
Tapi bagaimana dengan petani di Agam, nelayan di Mentawai, atau warga di jalan provinsi yang sering rusak karena longsor? Apakah mereka merasakan manfaat langsung dari tol tersebut? Atau justru hanya menikmati “cerita sukses” tanpa sentuhan nyata?
Hal serupa juga terlihat di Pelabuhan Panasahan. Secara strategis, pelabuhan ini bisa memperlancar distribusi hasil perikanan dan perdagangan antarwilayah. Tapi pertanyaan klasik kembali muncul: apakah fasilitas cold storage tersedia? Apakah akses jalan ke pelabuhan memadai? Apakah ada program pendampingan nelayan agar mereka bisa mengakses pasar baru? Jika tidak, pelabuhan bisa berakhir menjadi “monumen” tanpa aktivitas berarti.
Tiga Persoalan Kritis dalam Pembangunan Infrastruktur Sumbar 2025
1. Prioritas Proyek Besar vs Kebutuhan Dasar
Proyek tol dan pelabuhan memang penting. Tetapi jangan lupa, jalan desa, irigasi pertanian, dan air bersih adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat. Menurut catatan Bappeda, sebagian besar desa di Sumbar masih menghadapi keterbatasan akses jalan memadai, terutama di kawasan 3T.
Di sinilah muncul paradoks: proyek besar dengan nilai triliunan mendapat sorotan, sementara perbaikan jalan desa yang hanya butuh miliaran kadang tersisih. Akhirnya, ketimpangan antarwilayah tetap menganga.
2. Ketimpangan antara Pembangunan Baru dan Pemeliharaan
Infrastruktur tidak berhenti pada peresmian. Jalan tol, jembatan, atau pelabuhan memerlukan operasi dan pemeliharaan (O&M) yang berkelanjutan. Sumbar adalah daerah rawan longsor, banjir, dan erosi. Tanpa alokasi pemeliharaan yang memadai, infrastruktur baru bisa cepat rusak dan membebani anggaran.
Sayangnya, laporan anggaran daerah jarang menyebut porsi jelas untuk O&M. Padahal, jika pemeliharaan diabaikan, proyek besar bisa menjadi “proyek mati” dalam hitungan tahun.
3. Kualitas Perencanaan Spasial dan Mitigasi Bencana
Infrastruktur harus dirancang dengan memperhitungkan risiko bencana dan tata ruang. Sumbar punya topografi bergunung dan garis pantai panjang yang rawan gempa dan tsunami. Jika jalan atau pelabuhan dibangun tanpa kajian mendalam (AMDAL, mitigasi risiko), maka manfaatnya bisa kalah besar dibanding potensi kerugiannya.
Beberapa bypass yang dibangun di Padang, misalnya, memang memperlancar lalu lintas. Tetapi apakah sudah disertai drainase memadai untuk mencegah banjir? Jika tidak, jalan bisa berubah jadi kolam saat hujan lebat.
Studi Kasus: Tol Padang–Sicincin
Tol ini adalah proyek “primadona” Sumbar 2025. Bagi wisatawan, investor, dan warga kota, ia menghadirkan efisiensi luar biasa. Namun, agar manfaatnya merata, ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab:
- Apakah biaya tarif tol terjangkau bagi sopir angkutan barang dan petani kecil yang ingin membawa hasil panen?
- Apakah akses dari jalan desa ke pintu tol sudah memadai, atau justru membuat desa tetap terisolasi?
- Apakah ekonomi lokal (rest area, UMKM, pasar) dilibatkan dalam rantai manfaat tol?
Jika tidak, tol hanya akan jadi “jalan pintas” bagi segelintir kalangan—bukan motor pertumbuhan inklusif.
Studi Kasus: Pelabuhan Panasahan
Dengan dana sekitar Rp97 miliar, pelabuhan ini diharapkan jadi penghubung laut yang vital. Namun pelabuhan bukan sekadar dermaga. Ia butuh ekosistem: cold storage untuk ikan, pasar pelelangan yang terhubung, jalan akses yang bagus, serta SDM nelayan yang terlatih.
Tanpa itu semua, pelabuhan bisa macet sejak awal. Sejarah Indonesia sudah mencatat banyak pelabuhan dan bandara yang dibangun megah, tetapi sepi aktivitas. Jangan sampai Panasahan menambah daftar tersebut.
Rekomendasi: Agar Infrastruktur Tepat Sasaran
Agar pembangunan infrastruktur di Sumbar 2025 benar-benar tepat sasaran, ada beberapa rekomendasi penting:
- Gunakan indikator outcome, bukan hanya output.
Bukan sekadar “jalan terbangun 30 km”, tetapi “waktu tempuh petani ke pasar berkurang 50% dan pendapatan meningkat 20%”. - Alokasikan anggaran pemeliharaan secara jelas.
Minimal tetapkan persentase khusus untuk O&M, dan laporkan realisasinya setiap tahun. - Integrasikan proyek besar dengan infrastruktur pendukung.
Pelabuhan harus disambungkan dengan jalan kecil, pasar, dan cold chain. Tol harus dihubungkan dengan UMKM lokal. - Prioritaskan daerah 3T.
Alihkan sebagian dana high-visibility projects ke pembangunan jalan desa, irigasi, dan air bersih di Mentawai atau wilayah terpencil lain. - Transparansi dan partisipasi publik.
Libatkan masyarakat dalam evaluasi proyek, dari tahap perencanaan hingga operasional.
Penutup: Infrastruktur Harus Membumi
Infrastruktur memang penting, bahkan vital. Tetapi ia bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sumatera Barat di 2025 berada di persimpangan: apakah memilih jalan pembangunan yang berorientasi pada pencitraan—dengan proyek-proyek besar yang hanya indah di brosur? Ataukah memilih pembangunan yang membumi, menjejak pada kebutuhan nyata masyarakat, meski mungkin kurang “wah” untuk dipublikasikan?
Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan wajah Sumbar dalam 10–20 tahun mendatang. Jika infrastruktur dibangun dengan hati-hati, inklusif, dan berbasis kebutuhan rakyat, maka ia bisa jadi motor pemerataan ekonomi dan ketahanan sosial. Tapi jika tidak, ia bisa jadi beban, bahkan “monumen” tanpa makna.
Sumber:
- BPIW Kementerian PUPR. Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Sumatera Barat 2025–2034. ↩ ↩2
- DPRD Provinsi Sumbar. Keputusan APBD Perubahan Sumatera Barat 2025. ↩
- Hutama Karya & Kementerian PUPR. Laporan peresmian Jalan Tol Padang–Sicincin, Agustus 2025 (diberitakan oleh Detik, 2025). ↩ ↩2 ↩3
- Kementerian Perhubungan RI. Rencana Anggaran Pengembangan Pelabuhan Panasahan Painan 2025 (diberitakan oleh Antara News, 2025). ↩ ↩2
- Bappeda Sumatera Barat. Laporan Kinerja Daerah 2024. ↩
- Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat. Profil Desa 2023. ↩
- Pemerintah Provinsi Sumbar. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024. ↩
- BPBD Sumbar. Data Daerah Rawan Longsor 2024. ↩
Artikel opini ini diterbitkan pertama kali di http://www.kabasurau.co.id